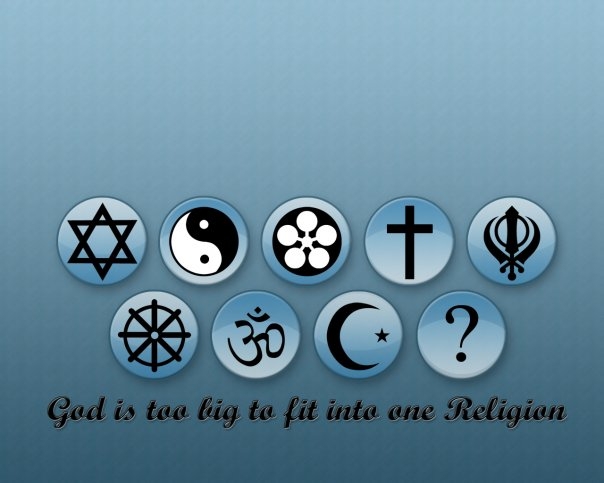
Saya terlahir di keluarga yang majemuk. Ayah seorang Syiah totok, ibu Sunni (Sunni NU yang ikut kebanyakan orang di kampung). Kakak saya yang pertama dan kedua adalah pengikut garis keras DI (Darul Islam) yang tegar dan kukuh pada pendiriannya untuk mendirikan negara Islam. Katanya sih melanjutkan perjuangan Kartosuwiryo. Wahabi-lah bisa dibilang begitu.
Adik saya dua, dua-duanya ikut muslim kebanyakan di kampung (Majalengka Jawa Barat), Sunni NU bisa dibilang.
Ayah menganut syi’ah sudah lama hampir 20 tahunan. Awalnya sama dengan kakak yaitu penganut aliran DI. Bahkan pentolan pertama di Majalengka, karena saya tahu pada waktu kecil ayah saya pernah dijemput oleh polisi dan ditahan selama seminggu karena mengadakan pengajian yang dihadiri mayoritas orang NII. Tuduhannya melakukan makar. Waktu dulu zaman Soeharto setiap pengajian dipantau. Melenceng sedikit langsung diciduk. Kemudian ayah pindah mengajinya dan langsung berubah drastis, baik dari cara ibadah maupun cara hidup (bersosialisasi dan sebagainya). Yang awalnya tak boleh bergaul dengan masyarakat luas, sejak menjadi Syiah menjadi lebih memasyarakat. Meskipun cara ibadahnya beda. Tapi ada perubahan pada paradigma berpikir.
Dari mana saya tahu bahwa ayah saya Syi’ah? Karena beliau mengatakannya langsung. Di samping tanda-tanda seperti cara sholatnya beda, banyak foto-foto Imam Khomeini di rumah, setiap tanggal 25 ramadhan demo Amerika ke Jakarta, dan banyak lagi tanda-tandanya.
Ibu saya tak terlalu mengerti apa syiah, apa sunni, apa wahabi secara mendalam, yang penting kata dia: hidup benar, sholat jangan ditinggalkan, jangan nipu orang, hidup harus jujur. Itu yang selalu ditanamkan ke anak-anaknya.
Saya sendiri ikut aliran mana? Saya sendiri lebih ikut ke ibu. Bahkan sering dicap tak punya pendirian. Karena mau ke Sunni ayo mau ke Syiah ayo, ke wahabi (yang DI sih ga mau ah), tapi yang penting jangan melanggar yang dilarang agama. Meskipun awalnya dari kecil saya disekolahkan di pesantren Wahabi yang DI sejak ayah masih ikut aliran itu sampai Tsanawiyah. Kemudian Aliyah di umum yang sunni dan kuliah di kampus yang mayoritas Syiah.
Buku-buku agama bacaan di rumah kami beragam, dari bukunya Sayyid Quthub sampai buku-bukunya Murtadha Mutahhari, Imam Khomeini, buku umum Quraish Shihab banyak. Saya baca saja semua. Toh ga rugi baca buku tambah ilmu. Jadi tahu bagaimana paradigma masing-masing. Bukan seperti kebanyakan orang yang sudah antipati dari awal sampai-sampai membaca bukunya pun tak mau. Lho, bagaimana bisa mengatakan salah kalau sumber aslinya saja tidak mau baca.
Boleh dikata: dunia saya adalah separuh syiah, separuh sunni, separuh wahhabi. Tapi akhirnya menyadari bahwa sikap ibulah yang lebih dewasa. Bahwa kebaikanlah patokan semuanya. Tak peduli mau sholatnya bagaimana, mau qunut atau tidak. Yang penting itu tadi: hidup bener, sholat jangan ditinggalkan, jangan nipu orang, hidup harus jujur.
Apakah kami sekeluarga tidak akur dan saling salah menyalahkan? Tidak sama sekali. Ayah yang syiah tidak melarang 2 anaknya ikut DI. Sudah besar ini, mereka sudah berkeluarga, silahkan saja. Meskipun banyak dirugikannya, karena sedikit-sedikit dengar anaknya tugas 2 minggu dakwah ke kalimantan, terpaksa kirim uang untuk anak-istrinya yang ditinggalkan. Nanti dengar kabar lagi kesulitan karena uangnya habis dipakai untuk acara dakwah, kirim uang lagi. Tapi namanya ke anak, dan meskipun berbeda pemahaman keagamaan, tak menyurutkan kasih sayang.
Lebaran setiap tahun kami sekeluarga selalu berkumpul. Ketika sholat berjamaah, imamnya sholat secara syiah (tangan lurus tidak bersedekap, selalu qunut di rakaat kedua, sujudnya harus pakai tanah atau kertas), makmumnya kami yang sunni dan kakak saya yang DI yang selalu melebarkan kaki sampai harus menyentuh kaki yang lain. Tapi tetap sholatnya selesai dan aman-aman saja. Ketika imam di rakaat kedua qunut, yang wahabi DI ya tak ikut, saya sih ikut saja masa imam begitu tak diikutin, adik-adik saya ada yang ikut ada yang gak. Biasa saja. Setiap tahun begitu.
Maka, saya seringkali heran kenapa orang lain tak bisa akur, ketika hanya memperebutkan masalah qunut, ketika memperebutkan masalah tayammum padahal di belakang rumahnya mengalir sungai deras. Kami aja sekeluarga bisa rukun kok. Syiah silahkan menjadi syiah, sunni silahkan menjadi sunni, wahabi silahkan menjadi wahabi. Di akherat nanti siapa yang benar terserah Tuhan saja. Karena La ilaha illallah, tidak ada yang absolut kecuali Allah, semua dari kita hanya merba-raba. Apa yang kita yakini benar belum tentu absolut benar.**[harja saputra]
———————-
**Ini bukan imajinasi, ini kisah nyata, saya tulis apa adanya.


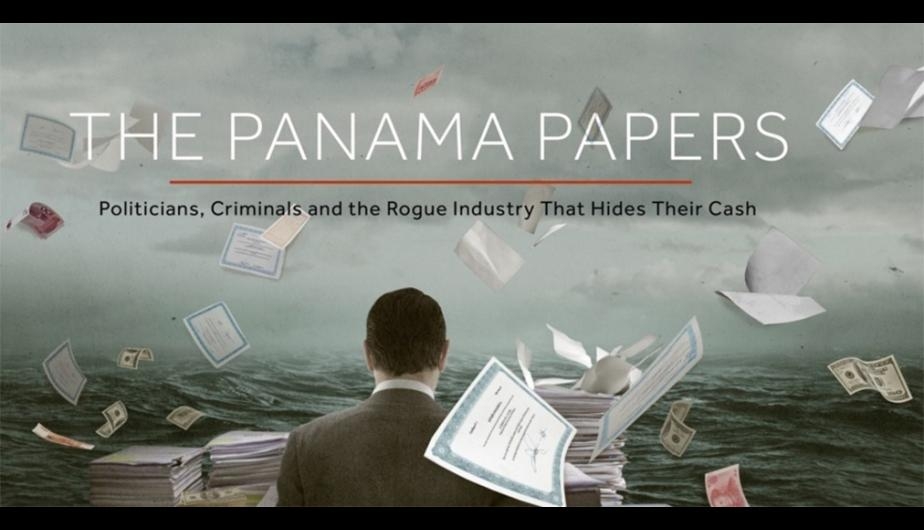



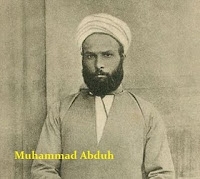
Lingkup keluarga bukanlah representasi lingkup masyarakat apalagi negara.
Anda bisa bayangkan menjadi seorang sufi atau pengamal dzikr lain yang ditebas lehernya oleh orang lain hanya karena beda paham. Look at Wahaby at 1700 M.
Disitu mungkin Anda bisa rukun kalau anda sudah hilang dari muka bumi. Fikiran itu sikap, bukan hal bisa diabaikan.