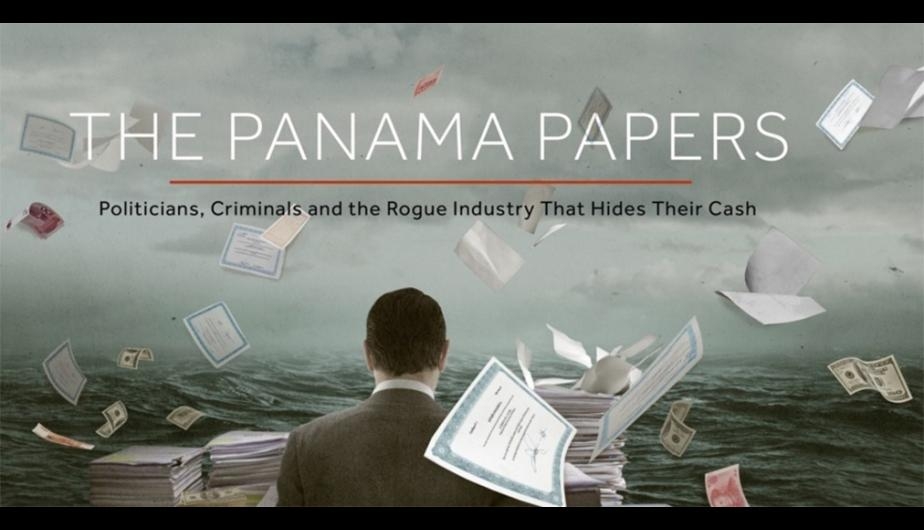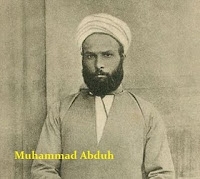Fenomena pengemis, anak jalanan, anak yatim piatu dan orang-orang yang butuh uluran tangan merupakan realitas yang sering kita jumpai. Baik yang ada di jalan, perumahan, di panti-panti asuhan, maupun tempat lain.
Ketika seseorang memberi kepada pengemis, misalnya, seringkali melihat terlebih dahulu kondisi fisiknya apakah benar-benar butuh bantuan atau hanya karena kemalasan. Tak jarang orang mengurungkan niat untuk memberi jika peminta-minta masih memiliki badan yang kuat yang seharusnya bekerja bukan meminta-minta.
Perkataan ini pun sering dilontarkan, “Jangan jadi pemalas, lebih baik cari kerja daripada meminta-minta, toh badan masih kuat, muda, dsb”.
Bahkan, tak jarang karena alasan: “Peminta-minta, anak jalanan tersebut ada yang mengkoordinir, dijadikan lahan bisnis, jadi buat apa kita memberi peluang bagi kemalasan”. Atau tidak memberi karena adanya larangan dari Peraturan Pemerintah Daerah bahwa memberi kepada peminta-minta akan diberikan hukuman.
Terlepas dari peraturan Daerah tersebut, karena Pemda pasti memiliki alasan tersendiri dalam mengeluarkan peraturan tersebut. Seperti mengganggu ketertiban umum, penyebab kemacetan, mentoleransi berkembangnya jumlah peminta-minta, dan lainnya. Pemda jelas memiliki otoritas dalam mengatur hal itu.
Namun, yang menjadi sorotan dalam tulisan ini adalah dari sisi kemanusiaan (humanisme). Pertanyaannya jangan dibenturkan apakah nilai kemanusiaan harus berbenturan dengan peraturan pemerintah. Bukan ke arah situ. Melainkan bagaimana sikap yang seharusnya dalam memberi.
Memberi (giving) dan berbagi (sharing) adalah inti dari kehidupan. Bahkan, pakar psikologi ada yang mengatakan, bahwa kebahagiaan yang sejati adalah ketika kita memberi dan berbagi dengan orang lain.
Ketika kita memberi tetapi dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka hal ini masih berada pada level “pemberi pemula”, karena didorong oleh persepsi terhadap apa yang dipahami mengenai standar kelayakan siapa saja yang harus diberi. Sementara persepsi adalah ordinal, artinya setiap orang berbeda-beda standarnya. Interval penilaian siapa saja yang layak sangat beragam. Dari skala sangat layak, layak, tidak layak, dan skala-skala yang sangat variatif.
Dengan kata lain, ketika perbuatan kita digerakkan oleh persepsi karena pengaruh dari obyek yang berada di luar maka perbuatan kita tidak lagi otentik, karena standarnya adalah adanya stimulus. Ketika obyek di luar menjadi penggerak motif maka sesungguhnya tindakannya menjadi tidak independen. Maka, di saat obyeknya berbeda maka perlakuannya pun akan berbeda.
Dalam perspektif psikologi kontemporer, kebahagiaan tidak akan tercapai kalau seseorang masih bertindak karena murni dari adanya stimulus dari obyek di luar diri kita. Karena kebahagiaan sesungguhnya tidak terletak pada dunia luar, tetapi ada di dalam diri kita.
Kaitannya dengan memberi, ketika memberi karena hanya kasihan melihat kondisi tubuh dan lainnya seperti contoh di atas, maka pemberian tersebut tidak akan memberikan pengaruh pada kebahagiaan si pemberi.
Pada “level kemanusiaan” memberi hendaknya dilakukan karena keyakinan bahwa memberi adalah suatu kebaikan. Tidak ada motif lain lagi selain keyakinan pada nilai kebaikan. Motif ingin memperoleh kebahagiaan setelah memberi pun tetap saja motif subyektif. Pada level ini motif kebahagiaan tidak lagi dipertimbangkan. Murni karena “memberi adalah kebaikan absolut”, memberi adalah memberi.
Implementasinya, memberi pada peminta-minta dilakukan karena keyakinan bahwa memberi adalah baik. Apakah mereka masih mampu bekerja, disalahgunakan, atau pertimbangan-pertimbangan lain, itu urusan mereka sebagai penerima.
Ketika setiap orang patokannya adalah nilai-nilai yang universal, yaitu kebaikan, maka peminta-minta pun meminta hanya karena faktor kebaikan. Bahkan di satu titik tidak akan lagi ada peminta-minta karena meminta itu bukan kebaikan.**[harja saputra]