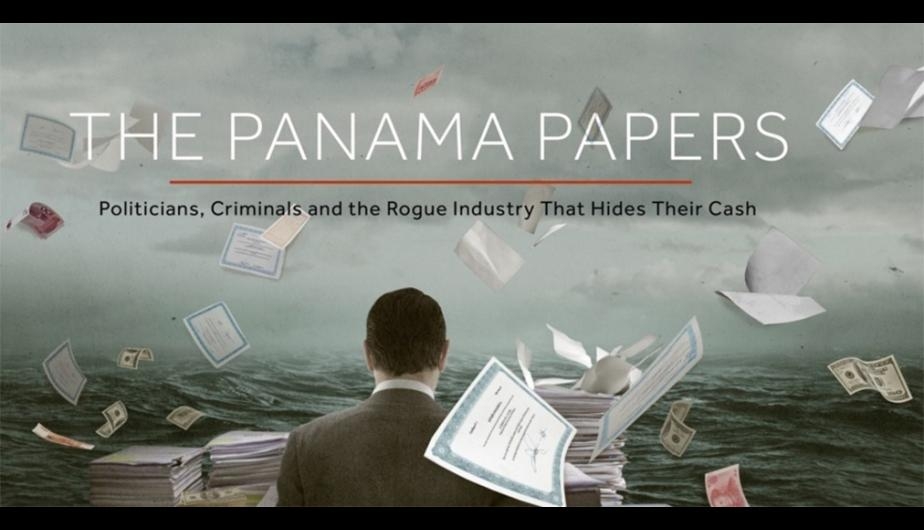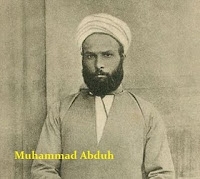Bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriyah dalam kalender Jawa disebut dengan Bulan Suro. Saat malam 1 Suro tiba, masyarakat Jawa umumnya melakukan ritual tirakatan, lek-lekan (tidak tidur semalam suntuk), dan tuguran (perenungan diri sambil berdoa). Bahkan sebagian orang memilih menyepi untuk bersemedi di tempat sakral.
Ritual 1 Suro telah dikenal masyarakat Jawa sejak masa pemerintahan Sultan Agung (1613-1645 Masehi). Saat itu masyarakat Jawa masih mengikuti sistem penanggalan Tahun Saka yang diwarisi dari tradisi Hindu. Sementara itu umat Islam pada masa Sultan Agung menggunakan sistem kalender Hijriah (sumber dari sini).
Ada pertanyaan mendasar yang patut dicermati: “Apa makna Suro? Apa makna di balik penamaan bulan Suro?”
Suro berasal dari kata “Asyuro” yang berarti “sepuluh”, yaitu merujuk pada tanggal 10 Muharram. Tentu bukan tanpa alasan ketika penanggalan Jawa menamakan bulan pertama dengan nama Suro. Peristiwa apa yang terjadi pada Asyuro (10 Muharram)? Terdapat dua pandangan berbeda yang bertolak belakang mengenai hal ini.
Pertama, dalam sebagian pendapat peristiwa Asyura diidentikkan dengan hari kemenangan sehingga dirayakan dengan kemeriahan. Dan ini yang dipraktekkan oleh beberapa kalangan, bahkan pada tanggal 1 Muharram kemarin, anak saya yang sekolah di TK diadakan lomba-lomba dengan tema di spanduknya “Muharram Ceria”.
Kedua, Asyura dimaknai sebagai hari kesedihan. Ini merujuk pada peristiwa pembantaian keji cucu Rasulullah Saw, yaitu Husein ibn Ali ibn Thalib ra, di mana ia disembelih oleh para pengikut Yazid ibn Muawiyyah (anak dari Muawiyyah sahabat Nabi).
Ke manakah filosofis penamaan Suro dari kalender Jawa berkiblat, apakah ke yang pertama atau kedua? Kalau dikatakan sebagai bulan keceriaan, tentu peringatan 1 Suro akan berbeda peringatannya. 1 Suro lebih condong ke pemaknaan kesedihan, yaitu mengacu ke peristiwa kedua. Ini bisa dibuktikan dari budaya yang lain. Di dalam budaya Sunda dikenal juga ada budaya “Bubur Sura” begitu juga di budaya Jawa hampir sama disebut dengan “Bubur Suro”. Bubur Sura terdiri dari dua warna: bubur merah dan bubur putih. Jika digali lagi, apa makna bubur merah dan bubur putih, bubur merah menandakan keberanian yaitu merujuk pada perjuangan Husein Ibn Ali di padang Karbala, hingga kepalanya diarak oleh pasukan Yazid. Adapun bubur putih pertanda kesucian, yaitu pada sosok Hasan Ibn Ali (kakak Husein ibn Ali).
Banyak budaya-budaya di tanah air yang mengacu pada peristiwa itu. Tari Saman Aceh misalnya, adalah tari kesedihan, hampir sama dengan budaya “maktam” (menepuk-nepuk dada dalam tradisi memperingati kesyahidan cucu Rasulullah, Husein ibn Ali). Bahkan, dalam budaya suku di Papua ada tari khas yang disebut yang menggambarkan peperangan di padang Karbala. Semua budaya ini pernah dipertunjukkan di Islamic Center Jakarta Utara, 4 tahun yang lalu, kebetulan saya sebagai Show Directornya.
Dari semua budaya-budaya di atas, maka bukan tanpa alasan beberapa pihak mengatakan bahwa Islam yang dibawa ke Indonesia oleh para wali terdahulu adalah Islam Syiah hanya saja berbeda dari negeri asalnya, terjadi akulturasi dengan budaya lokal. Gus Dur bahkan pernah mengatakan bahwa budaya Syiah dan budaya NU tak jauh berbeda, “NU adalah Syiah tanpa imamah”. Pendapat Gus Dur ini dibenarkan juga oleh Said Aqil Siradj pada sebuah seminar yang saya sempat hadiri.
Terlepas dari Syiah atau Sunni, yang pasti jika sudah menyangkut masalah ini biasanya terdapat perdebatan sengit, yang pasti adalah bahwa penghayatan nilai-nilai keagamaan harus berujung pada aksi riil bukan hanya peringatan semata.**[harja saputra]